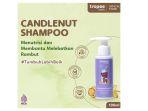Kopi Gayo
Mantra Kopi Gayo Atau Doa Ni Kupi, Dahulu Dibaca Saat Menanam, Nyerlak Atau Mangkas
Istilah Sengkewe ini ditemukan dalam teks "doa ni kupi" atau "mantra kopi" yang dahulu sering dibacakan oleh para petani kopi gayo.
Penulis: Fikar W Eda | Editor: Zainal Arifin
Tak ada catatan pasti, kapan dan kapan tanaman kopi tumbuh di bumi Gayo.
Istilah “kawa” atau “sengkawa” ini juga disinggung oleh C. Snouck Hurgronje, penulis Belanda dalam bukunya “Het Gajoland en Zijne Bewoners”.
Buku ini terbit pertama kali di Batavia pada 1903.
Kemudian diterbitkan ulang dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “Gayo Masyarakat dan Kebudayaannya Awal Abad ke-20” oleh Hatta Hasan Aman Asnah, PN Balai Pustaka, 1996, halaman 254.
Menurut Snouck Hurgronje, saat Belanda datang, kopi sudah tumbuh di Gayo.
C. Snouck Hurgronje mengungkapkan rasa herannya karena di tanah Gayo dijumpai batang kopi.
“Darimana asalnya, seorangpun tidak ada yang tahu. Sepanjang ingatan, tidak seorangpun mengaku pernah menanam kopi, dan menganggap bahwa tanaman ini tanaman liar,” tulis C. Snouck Hurgronje.
Masih menurut C. Snouck, masa itu orang mengambil batang atau cabang tanaman kopi untuk pagar (peger) kebun.
Buah kopi yang masak dibiarkan saja dimakan burung, kemudian burung itulah yang menyebarkan kopi.
“Orang Gayo sendiri tidak tahu bahwa kopi itu bisa diolah menjadi minuman segar. Yang mereka tahu hanya memanggang daunnya yang kemudian dijadikan teh,” kata C. Snouck Hurgronje.
Ini artinya, bahwa kopi telah tumbuh di dataran tinggi Gayo sebelum Belanda menjejakkan kaki kawasan itu pada 1904.
Dengan demikian tidak ada alasan lagi, kalau ada yang mengatakan bahwa kopi dibawa oleh Belanda ke Gayo.
Di banyak publikasi tentang kopi, selalu disebutkan bahwa kopi pertama kali masuk ke Indonesia tahun 1696 melalui Batavia (sekarang Jakarta), dibawa oleh Komandan Pasukan Belanda Adrian Van Ommen dari Malabar – India.
Ditanam dan dikembangkan di tempat yang sekarang dikenal dengan Pondok Kopi -Jakarta Timur, dengan menggunakan tanah partikelir Kedaung.
Sayangnya tanaman ini kemudian mati semua oleh banjir, maka tahun 1699 didatangkan lagi bibit-bibit baru, yang kemudian berkembang di sekitar Jakarta dan Jawa Barat antara lain di Priangan, dan akhirnya menyebar ke berbagai bagian dikepulauan Indonesia seperti Sumatera, Bali, Sulawesi, dan Timor.